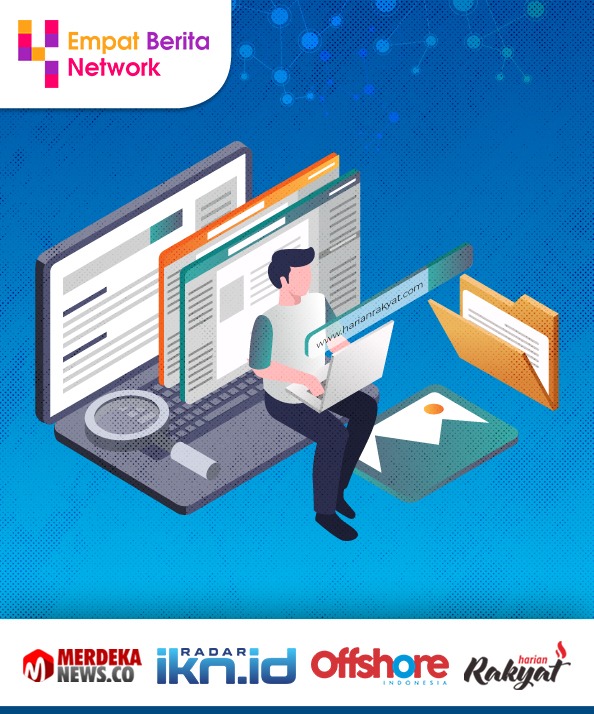Jelang Lebaran, mudik. Tradisi kita. Tapi, sedikit yang tahu, bahwa mudik di Jawa Pos, unik. Saya berkarir jurnalistik 24 tahun (1984-2008) di situ. Punya kenangan. Lucu-lucu.
--------------
Suatu hari di akhir Ramadhan 1995.
Wartawan Foto Jawa Pos (JP) Umar Fauzi, menghadap Redaktur Pelaksana JP, Nani Wijaya di kantor JP Jakarta, Jl Prapanca Raya 40.
Umar bicara pelan. Seolah berbisik. Kepada Nani. Saya (saat itu wartawan JP bidang ekonomi) tak mendengarnya.
Tapi, saya dengar jawaban Nani yang keras:
“Apa? Mudik? Kamu kayak babu aja, Mar…”
Umar izin libur mudik. Kena tohok telak.
Sesuai jadwal, dia termasuk anggota redaksi JP yang dilarang libur Lebaran. Fotografer penting. Tapi, dia ngotot nego, izin.
Maka, jawaban Redpel begitu ‘menusuk’.
Teman-2 wartawan JP lainnya, termasuk saya, tertawa (dalam hati): Gue bilang juga ape?
Seketika... Umar melengos. Wajah cemberut. Bures.
Dia tinggalkan Nani, yang belum selesai bicara. Ngeloyor pergi. Walk-out.
Akhirnya, dia tetap tugas saat Lebaran. Mau gimana lagi?
Umar (waktu itu) satu-satunya wartawan foto JP Jakarta. Sebagian kawannya, wartawan tulis, termasuk saya, boleh mudik. Bergiliran.
Umar, ibarat ikan tidak paham kondisi air. Tempat dia hidup. Akibatnya, kepenthok. Ikan yang kepenthok.
---------------
 Djono W. Oesman
Djono W. Oesman
VERSI LAIN
Setahun sebelumnya. Jelang Lebaran 1994. Hal mirip terjadi pada Zarmansyah (Kepala Biro Redaksi JP Jkt).
Zarman komandan wartawan JP di Jkt (saat itu jumlahnya 12 orang, termasuk saya dan Umar). Posisi dia berada di bawah Redpel Nani (berbasis di Surabaya, kebetulan saat itu di Jkt).
Kabiro termasuk dilarang libur Lebaran. Bolehnya, pasca Lebaran.
Namun, Zarman (asal Surabaya) tak kurang akal. Jelang Lebaran dia minta izin. Ke Nani juga.
Saya, tiga meter-an di dekat Nani. Mendengar pembicaraan mereka. Tidak nguping, ya... sebab, ini di area terbuka.
Zarman:
“Nenek isteri saya, sakit keras di desa, Mbak. Saya izin libur.”
Nani memandang Zarman dengan tatapan tajam. Kayaknya, Nani berpikir. Bahasa apa yang akan dia ucapkan? Nadanya bagaimana? Intonasinya?
Ketemu-lah... Dengan cepat. Nani balik bertanya:
“Nenek daripada isterimu?"
"Bukan nenekmu?"
"Lha... Bagaimana, kalau yang sakit nenek daripada saudara isterimu?”
Bertubi-tubi. Kombinasi: Jab, upper-cut, straight... Ludes, brow...
Zarman cemberut. Saya gak berani ketawa. Menahan keras. Dalam hati: Paraturan dilawan…
---------------
 DWO, Siswo Hadi dan Agus Jauhari yang juga siap-siap mudik lebaran
DWO, Siswo Hadi dan Agus Jauhari yang juga siap-siap mudik lebaran
DARI PRASEJARAH sampai WHATSAPP
Di satu sisi, saya memaknai dua peristiwa tersebut sebagai: Kasih sayang Nani (mewakili JP sbg perusahaan pers) kepada wartawan JP.
Maksudnya: Wartawan janganlah kolokan. Sayang, jika potensi wartawan yang begitu besar, lalu minta libur.
Apalagi mudik, bagi wartawan JP di Jkt asal Jatim. Butuh minimal 4 hari. Sebab, kemampuan finansial kami hanya naik KA atau bus. Belum airline.
Sayang 'kan... karir wartawannya? Kapan jadi wartawan besar kalau suka libur? (perspektif perseroan)
Juga sayang perusahaan JP, jika sering ditinggal wartawan libur? (perspektif borjuis).
Di sisi lain, saya juga terpengaruh beberapa buku.
Sekarang main literatur, nih...
Berdasarkan Ensiklopedia Sejarah Indonesia, kebiasaan mudik sudah ada sejak pra-sejarah.
Disebutkan, manusia Indonesia keturunan Melanesia. Sebagian berasal dari Yunan, China.
Nenek moyang bangsa Indonesia adalah pengembara. Pemberani. (Nenek moyang-ku... seorang pelaut...)
Di sini, mereka mencari nafkah dengan berburu hewan. Menyebar ke berbagai tempat. Nomaden.
Manusia pra-sejarah punya momentum tertentu untuk kembali ke daerah asal. Pra-sejarah. Pra-tradisional. Penyembahan arwah nenek moyang, jadi dasar mereka pulang ke tanah asal.
Pada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik, mereka berbondong-bondong mudik.
Agama di Indonesia zaman itu belum berkembang. Animisme - dinamisme, latar belakang mereka mudik.
Lalu berkembang. Zaman Kerajaan Majapahit, kegiatan mudik lebih jelas.
Pasca panen raya, para punggawa dari seluruh negeri (Tumasek, Filipina, Malaysia, Thailand, Brunei, Madagaskar, saat itu semuanya wilayah Majapahit) beramai-ramai mudik ke Jawa.
Bersatu mudik. Sekedar bertemu sanak saudara di pesta pasca panen raya. Melepas rindu, setahun sekali.
Berkembang lagi. Islam masuk Indonesia. Mudik tetap ada. Tapi berubah bentuk.
Jika manusia prasejarah, mudik, menyembah arwah. Lalu zaman Majapahit, di panen raya. Setelah masuknya Islam, momen Idul Fitri. Berlanjut hingga kini.
Tradisi mudik merupakan wahana klangenan. Jembatan nostalgia dengan masa lalu.
Pemudik (pasti dari desa), rindu bercengkerama dengan romantisme alam desa.
Dalam konsep anthropologi dikenal sebagai close coorporate community. Dalam sosiologi disebut: Akar budaya.
Gampangnya: Romantika nostalgik. Atau, rindu yang terkiwir-kiwir.
Sosiolog Pierre Bouerdieu (1930 - 2002) dari Prancis: Itu membawa manusia ke refleksi jati dirinya.
Jati diri menyangkut: Pengetahuan, selera, makna lokasi desa yang didatangi. Juga kerabat yang dijenguk. (Scott Lash, Sosiologi Posmodern; 2004).
Dalam bahasa saya: "Dulu... sungai ini bersih. Sekarang, kok gini, ya..."
Atau: "Sego pecel Mbok Ra, apakah masih ada? Saya kangen, sampai ngimpi-ngimpi."
Bisa juga: "Diamput... Aku pengen nonton ludruk Tansah Tresno. Di mana, rek?"
Anthropolog Abraham Maslow (1908 - 1970): Mudik kebutuhan dasar manusia. Dengan begitu manusia bisa meninggalkan sementara, kepenatan di perkotaan. Dikotomi desa-kota.
Sosiolog Emile Durkheim (1859-1917) menyebutnya sebagai Solidaritas Organik. Mudik melanggengkan solidaritas. Sebelum Lebaran, orang terlalu sibuk. Kini bisa silaturrahim.
Tetapi, bukankah kini sudah modern?
Ada internet. Email, facebook, twitter instagram, whatsapp.
Bukankah, dunia sudah dalam genggaman HP?
Ya... ya... ya... Sosiolog UGM, Arie Sudjito, menjawab pertanyaan itu begini:
“Ada beberapa kelemahan teknologi.”
Dia menyebut 4 hal yang membuat mudik tak tergantikan teknologi.
(1) Mencari berkah. Bersilaturahmi mendatangi orangtua, kerabat, tetangga.
(2) Terapi psikologis. Refreshing dari rutinitas pekerjaan sehari-hari di kota.
(3). Mengingat asal usul.
(4) Unjuk diri kepada sanak-kerabat, bahwa mereka sukses di kota besar. Memberi “uang receh” kepada anak-anak sebagai sedekah (mungkin juga pamer).
Pamer, perwujudan eksistensi diri. Bahwa setiap individu butuh pengakuan sosial. Memompa motivasi kelompoknya. Agar sukses juga.
-----------
WHADUH… KEPERGOK DAHLAN
Kenangan saya melayang lagi. Meliuk-liuk. Berkelana. Hinggap di jelang Lebaran 2008.
Saat itu saya Redaktur Pelaksana Indopos, Jakarta (koran, anak perusahaan JP).
Saya main ke kantor JP Jakarta. Kantor Indopos dan JP, sama-sama di lantai 10 Graha Pena, Kebayoran Lama, Jkt. Cuma dibatasi partisi.
Saya ngobrol dengan wartawan senior, Agus Sudjoko (inisial di JP: ADO).
ADO: “DWO (panggilan saya), Lebaran nanti, kamu mudik?”
Saya belum sempat menjawab, dia sudah nyerocos:
“Aku, meskipun gak mudik, minta izin cuti, ah…”
ADO lantas merinci. Cerita-cerita sulitnya wartawan JP minta izin libur. Sulit sekali.
Saya menyimak. Diam.
Saya pahami, ceritanya sekadar menyatukan paham. Ini konflik kuno: Proletar versus Borjuis. Dan, kodratnya: Proletar harus bersatu paham. Melawan Borju.
Mendadak, Pak Dahlan muncul. Padahal, jarang-jarang dia ke Jakarta. Ini sekonyong-koder... Sekonyong-konyong, tanpa kode-kode.
Pak Dahlan keluar dari lift lantai 10.
Berjalan cepat ke arah kami. Sidak, gitu-lah.
Pak Dahlan berkalungkan jaket, mendekati kami. Gayanya seperti anak muda. (Saat itu dia belum tua, walau gak muda banget).
Kebetulan, kami duduk ngobrol. Berjarak sekitar 10 meter dari pintu lift. Saya lihat dia keluar pintu lift. Sendirian.
Melenggang-lah... dia ke arah kami.
Dia berhenti, persis di belakang ADO, yang serius bicara ke saya. Alamaaak... bahaya ini.
ADO tak menyadari kehadiran Pak Dahlan. Dia terus nyerocos:
“Sejak dulu, kita ini dipersulit kalau minta izin cuti…..”
ADO… ADO…. ADO…. Saya garuk-garuk kepala.
Saya mencari cara cepat menghentikan ADO. Kalau stop langsung, gak etis. Ada Dahlan berhadapan dengan saya.
Saya tendang-tendang kaki ADO. Kode keras... mayday... mayday... mayday...
Tapi, ADO menjawab kilat:
“Lho, ini kenyataan kan? Kenyataan... Kita diperkuda, lho.”
Mati aku…. ancuuuuur…..
Gak sabar. Saya potong: “Pak Dahlan…”
Saya berdiri, mengulurkan tangan. Berniat menyalami Pak Dahlan.
Suasana langsung kacau. Belingsatan.
ADO berdiri menoleh ke belakang. Langsung, berhadapan hidung dengan Pak Dahlan.
Mereka saling berpandangan.
O, ya... Uluran tangan saya ke Pak Dahlan belum diterima. Wajah Dahlan mengkerut.
Sedetik, Pak Dahlan bergerak menjauh.
Terpaksa... Saya menarik tangan lagi. Gak jadi salaman.
Pak Dahlan. Beberapa langkah. Berhenti. Membalikkan badan ke saya dan ADO. Saya rasakan aura panas. Hawa membara.
Kami siap-siap. Menunggu. Apa yang terjadi?
Dia berucap: “Silakan... siapa yang mau libur terus?”
Suara Dahlan kenceng banget. Cempreng tapi bertenaga. Pecah pol.
Kantor Jawa Pos yang tanpa sekat, membuat itu membahana. Mengagetkan semua jurnalis yang tekun bekerja.
Hebatnya, ADO tidak menunduk. Dia tegar. Atau mungkin ditegar-tegarkan.
Jangan salah, ADO, pelatih pencak silat, lho... Dia menatap mata Pak Dahlan. Wah... bakal seru, neeh...
Ditatap begitu, Dahlan tambah meluap. Tambah muntab. Dia bicara, lebih kencang lagi. Begini:
“Hayo…. Siapa mau libur terus? Siapa... Silakan. Saya tidak melarang,” ucap Pak Dahlan, berantakan, berceceran.
Saya tangkap, teriakan ini ditujukan kepada semua. Sudah membias. Meluas.
Para wartawan bengong. Kaget. Gak tau asal-muasalnya.
Mereka heran melihat Pak Dahlan. Ujung-ujungnya, mereka memandang saya dan ADO (yang akhirnya menunduk). Suasana kaku. Beku.
Beberapa detik, Pak Dahlan jalan. Masuk lift.
Pergi meninggalkan kantor. Cabut begitu saja. Entah kemana.
Saya buru-buru ke meja saya. Kembali kerja. Teman-teman berkerumun, bertanya-tanya keheranan.
Itu nostalgia. Zaman Dahlan masih di JP.
Kini, juga menjelang Lebaran.
Mengenang itu, saya bergumam: “Kini saya dan ADO sudah tidak di JP. Bebas merdeka. Ayo, kita mudik….
Tarik.... mang ADO...
(Jakarta, jelang Lebaran, 10 Agustus 2012. Sumber : facebook.com Djono W. Oesman) (***)
-
 Capres Pemberani di Zaman Itu
Kontestasi Jokowi vs Prabowo Subianto, heboh. Saya flashback pengalaman di Jawa Pos. Terkait Capres juga. Cuma, ini fokus karya jurnalistik. Bukan politik.
Capres Pemberani di Zaman Itu
Kontestasi Jokowi vs Prabowo Subianto, heboh. Saya flashback pengalaman di Jawa Pos. Terkait Capres juga. Cuma, ini fokus karya jurnalistik. Bukan politik.